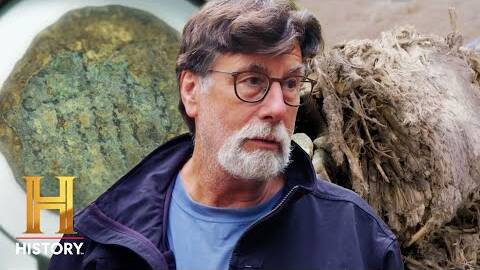Bukan Muda-mudi Hilang Arah
Medium | 21.12.2025 22:54
Bukan Muda-mudi Hilang Arah
Bulan lalu aku mengikuti sebuah lokakarya di Bali, sekilas terdengar serius, tapi sebenarnya ini lebih seperti matchmaking—ruang temu bagi orang muda yang sadar bahwa kerja isu tidak pernah benar-benar bisa dilakukan sendirian.
Sesi Adaptasi
Sebagian besar peserta adalah generasi Z. Mereka hadir dengan energi yang nyaris tak habis mulai dari bincang heboh di sela-sela istirahat, mendokumentasikan kegiatan, memproduksi konten, sekaligus tetap responsif terhadap diskusi dalam forum. Situasi tersebut membuat aku sadar kalau caraku berada di ruang kolektif tidak bertumpu pada kecepatan atau keriuhan.
Jujur, belakangan aku mudah lelah oleh limpahan informasi—baik dari ponsel maupun dari materi yang bertubi-tubi. Tuntutan untuk terus responsif sering membuatku memilih diam, bukan karena tidak peduli, melainkan karena sedang memproses. Aku lebih nyaman mendengar, mengamati, dan merefleksikan ulang apa yang kudengar.
Perbedaan tempo itu tidak membuatku merasa canggung. Justru di situlah aku merasa cukup. Di antara orang-orang yang memiliki tenaga lebih besar, aku tidak merasa tertinggal. Kami hanya berkontribusi dengan cara yang berbeda. Mereka menyuarakan, aku menyimpan. Mereka memproduksi, aku merangkai pemahaman.
Menemukan Ruang Aman
Di sela-sela waktu kami banyak ngobrol, salah satu kawan sempat bertanya soal identitasku. Aku menjelaskan bahwa Padang adalah ibu kota Sumatera Barat, sedangkan Minangkabau adalah suku mayoritas di wilayah tersebut. Penjelasan sederhana itu berkembang menjadi obrolan tentang bagaimana identitas kerap disederhanakan oleh pandangan luar, hingga asal muasal datangnya Islam ke Sulawesi Tengah.
Percakapan santai di luar sesi formal tidak berhenti pada isu yang sempit, tetapi meluas ke patriarki, keragaman gender dan seksualitas, relasi kuasa, hingga persoalan lingkungan dan deforestasi.
Sambil berendam dalam kolam renang kami bahkan saling berbagi cerita mengenai perjalanan gender dan relasi. Di ruang itu, aku dapat berbicara secara terbuka—mengenai preferensi seksual dan pola hubungan yang kupilih.
Itu pertama kalinya aku bicara secara terbuka ke manusia. Sebab di Padang, aku tidak yakin pemikiranku dapat diterima, padahal mereka yang menabukan kerjanya mengintai mangsa terdekat. (ah sudahlah lupakan saja mereka)
Selain itu ada batas-batas sosial yang membuat percakapan semacam itu terasa canggung. Dan justru di sini aku menemukan paguyuban aman untuk menjelaskan diriku apa adanya, tanpa perlu menyensor pengalaman personal.
Get powerpunkgvrl’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Subscribe
Subscribe
Bali dan Sumbar, Kontras dan Kekaguman
Bagian ini memperlihatkan sisi kekagumanku atau barangkali kenorakanku terhadap Bali, atau lebih tepatnya terhadap sistem yang menopang kerja-kerja komunitas dan organisasi di sana.
Seorang kawan yang telah beberapa tahun menetap di Bali pernah berkata, “memang rata-rata sudah seperti itu di sini.” Mungkin benar, atau mungkin aku hanya terbiasa hidup di kota yang standar keberlanjutannya terlalu rendah.
Hal-hal kecil justru terasa mencolok: pasta gigi yang tidak langsung diganti oleh housekeeping sebelum benar-benar habis, pemilahan sampah organik dan nonorganik, serta ruang kerja organisasi yang memilih tidak menggunakan AC yang selaras dengan nilai keberlanjutan yang mereka anut. Praktik-praktik ini tidak ditampilkan sebagai simbol moral, melainkan sebagai kebiasaan sehari-hari.
Kontras itu membuatku kembali mengingat kota Padang. Di sana, kepemilikan kendaraan masih menjadi penanda prestise; transportasi umum belum mampu menjadi pilihan yang layak; dan penggunaan pendingin udara seolah menjadi kebutuhan mutlak, bahkan untuk aktivitas yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Sampah tidak dipilah, sebagian dibuang ke sungai, sementara perusahaan turut menyumbang limbah industri ke aliran air yang sama. Sistem pengelolaannya rapuh dan tidak terintegrasi.
Upaya daur ulang pun berjalan sporadis. Untuk sampah plastik, praktik daur ulang lebih sering bergantung pada inisiatif individual, bukan dukungan sistemik. Hanya ada TPA, padahal ada limbah berbahaya seperti limbah pembalut sekali pakai, yang tidak pernah masuk dalam perbincangan kebijakan publik.
Padahal yang sering kita jargonkan untuk keberlanjutan adalah warga diminta bertanggung jawab secara individu. Tapi tidak ada infrastruktur yang memungkinkan perilaku berkelanjutan dijalankan secara kolektif.
Namun, satu kesamaan mencolok kedua daerah ini: eksploitasi ruang hidup tetap berlangsung, meskipun hadir dengan wajah yang berbeda. Di Bali, vila-vila milik warga negara asing telah tumbuh dan tersebar luas.
Di Mentawai, pola serupa mulai terlihat—tanah dibeli, ruang diubah untuk kepentingan pariwisata, dan warga lokal perlahan terdorong ke pinggir. Di Tua Pejat, seorang kawan pernah bercerita bahwa ia diusir WNA saat memancing di laut dekat sebuah vila, seolah ruang publik dapat diklaim sebagai properti komersial.
Lelah yang Dirindukan
Kontras dan kemiripan itu membuatku menyadari bahwa kekaguman dan kegelisahan bisa berjalan beriringan. Sepulang dari Bali, tubuhku benar-benar letih. Sakit perut dan flu menyerang secara bersamaan. Namun, kelelahan itu tidak kosong. Ada rasa utuh karena meski caraku hadir lebih sunyi, aku tetap menjadi bagian dari ruang bersama itu.
Bertemu dengan kawan-kawan yang sefrekuensi memberiku jarak dari rasa putus asa yang selama ini pelan-pelan mengendap. Mereka tidak selalu optimistis. Banyak di antara mereka juga mengeluhkan ketidakpastian, sulitnya mencari kerja, dan arah hidup yang terasa goyah. Aku menyadari dan belajar dari mereka bahwa keadaan boleh sulit, tetapi tidak harus dihadapi dengan menyerah.
Aku tidak merasa diarahkan, apalagi dinasihati. Aku hanya melihat bagaimana mereka tetap menentukan langkahnya masing-masing, sambil mengakui kerapuhan. Dari situ, keputusasaanku tidak hilang begitu saja, tetapi terkikis—cukup untuk memberiku ruang bernapas.
Karena itu, aku menantikan pertemuan selanjutnya. Bukan semata untuk mencari hibah. Melainkan untuk kembali berada di antara orang-orang dengan cara berpikir, keresahan, dan cara bertahan yang serupa.